DisusunOleh
:
Kelompok
4 (IlkomIII Jurnalistik)
Aprillia
Annisa
Faras
Tamimy
Maria
Ulfa
Mira
Fadilah
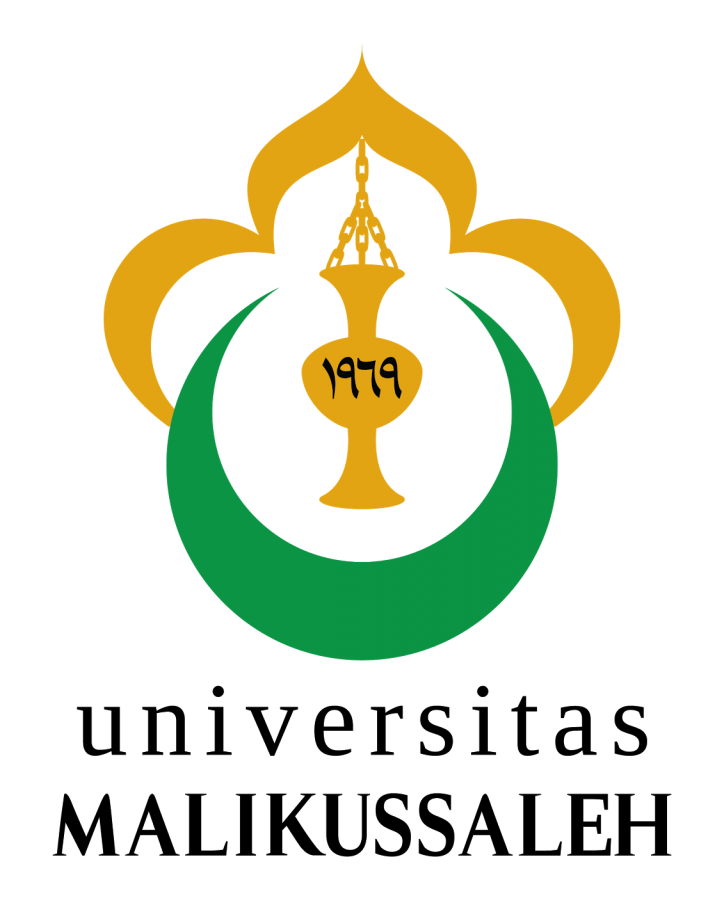
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2016
Segala
puji bagi Allah swt. yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk
menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem Kemasyarakatan Budaya Sunda” dengan
baik. Selanjutnya, salawat dan salam penulis sanjungkan kepada nabi Muhammad
saw. yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan
pengetahuan.
Makalah ini membahas tentang
bagaimana kebudayaan Sunda, apa saja hal yang dianggap tabu oleh masyarakat
Sunda, dan lain sebagainya.
Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Anismar sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Komunikasi
Lintas Budaya.
Makalah yang berjudul “Sistem
Kemasyarakatan Budaya Sunda” ini diharapkan dapat menjadi penunjang bagi
pembaca untuk mempelajari kebudayaan Sunda , bagaimana adat Sunda dan lain
sebagainya. Atas perhatian pembaca, penulis mengucapkan terima kasih.
Matang Glumpang Dua, 4 November 2016
Penulis,
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................
i
DAFTAR ISI.....................................................................................................................
ii
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang..............................................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah.........................................................................................
1
1.3 Tujuan Penelitian..........................................................................................
2
BAB II. Kajian Teoritis
2.1 Budaya Sunda...............................................................................................
3
2.2 Nilai Budaya Sunda......................................................................................
9
2.3 Kelebihan Budaya Sunda............................................................................. 9
2.4 Adat Istiadat Suku Sunda.............................................................................
10
2.5 Makanan Khas Sunda..................................................................................
19
2.6 Sistem Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial ............................................ 23
2.7 Bahasa dan Religius.....................................................................................
24
2.8 Hal-Hal yang Dianggap Tabu Oleh Masyarakat Sunda................................ 24
BAB III. Penutup
3.1 Kesimpulan..................................................................................................
26
3.2 Saran...........................................................................................................
26
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Sistem kekerabatan dan organisasi sosial,
Sistem kekerabatan merupakan bagian yang
sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem
kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur
sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial
yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan
perkawinan. Sedangkan organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.Bahasa adalah alat atau
perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau
berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat),
dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau
orang lain.
Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan
diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus
mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Bahasa memiliki
beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi
bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan
alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa
secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari,
mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk
mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang
di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, adat istiadat, norma, dan lain
sebagainya. Kebudayaan suatu suku adalah pencerminan atau tanda dari suku yang
bersangkutan, misalnya seperti budaya Sunda yang terkenal dengan keramahan dan
kesantunannya.
1.2
Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan
masalah sebagai berikut :
1.
Bagaimanakah kebudayaan
Sunda ?
2.
Apa saja nilai-nilai
yang terdapat dalam masyarakat Sunda ?
3.
Apa saja kelebihan
budaya Sunda ?
4.
Bagaimanakah
adat-istiadat suku Sunda ?
5.
Apa saja makanan khas
Sunda ?
6.
Bagaimana sistem
kemasyarakatan / organisasi sosial masyarakat Sunda ?
7.
Bagaimana bahasa maupun
religi yang terdapat dikebudayaan Sunda ?
8.
Apa saja hal yang
dianggap tabu oleh masyarakat Sunda ?
1.3
Tujuan Penelitian
Makalah
ini bertujuan agar pembaca dapat mengerti atau memahami tentang budaya Sunda
yang telah mendunia sekarang ini.
KAJIAN TEORITIS
A. Budaya
Sunda
Kebudayaan
Sunda adalah salah satu budaya di Indonesia yang berusia tua dibanding budaya
Jawa. Sunda merupakan budaya pada wilayah Barat pulau Jawa, namun seiring
berjalannya waktu budaya ini menjadi sangat terkenal. Sebagai suatu suku,
bangsa Sunda ialah cikal bakal peradaban di Nusantara. Dimulai dengan
berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Salakanagara dan Tarumanegara.
Sunda
berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur
kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai
jalan menuju keutamaan hidup. Dalam kebudayaan Sunda terdapat etos atau watak
tentang satu jalan menuju keutamaan hidup, diantaranya adalah :
- Cageur, yakni harus sehat jasmani dan rohani, sehat berpikir, sehat berpendapat, sehat lahir dan batin, sehat moral, sehat berbuat dan bertindak, sehat berprasangka atau menjauhkan sifat suudzan.
- Bageur yaitu baik hati, sayang kepada sesama, banyak memberi pendapat dan kaidah moril terpuji ataupun materi, tidak pelit, tidak emosional, baik hati, penolong dan ikhlas menjalankan serta mengamalkan, bukan hanya dibaca atau diucapkan saja.
- Bener yaitu tidak bohong, tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas pekerjaan, amanah, lurus menjalankan agama, benar dalam memimpin, berdagang, tidak memalsu atau mengurangi timbangan, dan tidak merusak alam.
- Singer, yaitu penuh mawas diri bukan was-was, mengerti pada setiap tugas, mendahulukan orang lain sebelum pribadi, pandai menghargai pendapat yang lain, penuh kasih sayang, tidak cepat marah jika dikritik tetapi diresapi makna esensinya.
- Pinter, yaitu pandai ilmu dunia dan akhirat, mengerti ilmu agama sampai ke dasarnya, luas jangkauan ilmu dunia dan akhirat walau berbeda keyakinan, pandai menyesuaikan diri dengan sesama, pandai mengemukakan dan membereskan masalah pelik dengan bijaksana, dan tidak merasa pintar sendiri sambil menyudutkan orang lain.
Suku
Sunda juga merupakan suku yang memiliki banyak kebudayaan daerah, diantaranya:
11. Pakaianadat Jawa Barat

Suku sunda mempunyai pakaian adat/tradisional yang sangat
terkenal, yaitu kebaya. Kebaya merupakan pakaian khas Jawa Barat yang sangat
terkenal, sehingga kini kebaya bukan hanya menjadi pakaian khas sunda saja
tetapi sudah menjadi pakaian adat nasinal. Itu merupakan suatu bukti bahwa
kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional.
22. Kesenian khas Jawa Barat
a.
Wayang Golek
Wayang Golek merupakan kesenian tradisional dari Jawa Barat yaitu kesenian yang menapilkan dan membawakan alur sebuah cerita yang bersejarah. Wayang Golek ini menampilkan golek yaitu semacam boneka yang terbuat dari kayu yang memerankan tokoh tertentu dalam cerita pawayangan serta dimainkan oleh seorang Dalang dan diiringi oleh nyanyian serta iringan musik tradisional Jawa Barat yang disebut dengan degung.
b.
Jaipong
Jaipong merupakan tarian tradisional dari Jawa Barat, yang
biasanya menampilkan penari dengan menggunakan pakaian khas Jawa Barat yang
disebut kebaya, serta diiringi musik tradisional Jawa Bart yang disebut Musik
Jaipong.Jaipong ini biasanya dimainkan oleh satu orang atau sekelompok penari
yang menarikan gerakan – gerakan khas tari jaipong.

c.
Degung
Degung merupakan sebuah kesenian sunda yang biasany
dimainkan pada acara hajatan. Kesenian degung ini digunakan sebagai musik
pengiring/pengantar. Degung ini merupakan gabungan dari peralatan musik khas Jawa
Barat yaitu, gendang, goong, kempul, saron, bonang, kacapi, suling, rebab, dan
sebagainya.Degung merupakan salah-satu kesenian yang paling populer di Jawa
Barat, karena iringan musik degung ini selalu digunakan dalam setiap acara
hajatan yang masih menganut adat tradisional, selain itu musik degung juga
digunakan sebgai musik pengiring hampir pada setiap pertunjukan seni
tradisional Jawa Barat lainnya.
d.
Rampak Gendang
Rampak Gendang merupakan kesenian yang berasal dari Jawa
Barat. Rampak Gendang ini adalah pemainan menabuh gendang secara bersama-sama
dengan menggunakan irama tertentu serta menggunakan cara-cara tertentu untuk
melakukannya, pada umumnya dimainkan oleh lebih dari empat orang yang telah
mempunyai keahlian khusus dalam menabuh gendang. Biasanya rampak gendang ini
diadakan pada acara pesta atau pada acara ritual.


e.
Calung
Di daerah Jawa Barat terdapat kesenian yang disebut Calung,
calung ini adalah kesenian yang dibawakan dengan cara memukul/mengetuk bambu
yang telah dipotong dan dibentuk sedemikian rupa dengan pemukul/pentungan kecil
sehingga menghasilkan nada-nada yang khas. Biasanya calung ini ditampilkan
dengan dibawakan oleh 5 orang atau lebih. Calung ini biasanya digunakan sebagai
pengiring nyanyian sunda atau pengiring dalam lawakan.


f.
Pencak Silat
Pencak silat merupakan kesenian yang berasal dari daerah
Jawa Barat, yang kini sudah menjadi kesenian Nasional. Pada awalnya pencak
Silat ini merupakan tarian yang menggunakan gerakan tertentu yang gerakannya
itu mirip dengan gerakan bela diri. Pada umumnya pencak silat ini dibawakan
oleh dua orang atau lebih, dengan memakai pakaian yang serba hitam, menggunakan
ikat pinggang dari bahan kain yang diikatkan dipinggang, serta memakai ikat
kepala dari bahan kain yang orang sunda menyebutnya Iket. Pada umumnya kesenian
pencaksilat ini ditampilkan dengan diiringi oleh musik yang disebut gendang
penca, yaitu musik pengiring yang alat musiknya menggunakan gendang dan
terompet.
g.
Sisingaan
Sisingaan merupakan kesenian yang berasal dari daerah Subang
Jawa barat. Kesenian ini ditampilkan dengan cara menggotong patung yang
berbentuk seperti singa yang ditunggangi oleh anak kecil dan digotong oleh
empat orang serta diiringi oleh tabuhan gendang dan terompet. Kesenian ini
biasanya ditampilkan pada acara peringatan hari-hari bersejarah.


h.
Kuda Lumping
Kuda Lumping merupakan kesenian yang beda dari yang lain,
karena dimainkan dengan cara mengundang roh halus sehingga orang yang akan
memainkannya seperti kesurupan. Kesenian ini dimainkan dengan cara orang yang
sudah kesurupan itu menunggangi kayu yang dibentuk seperti kuda serta diringi
dengan tabuhan gendang dan terompet. Keanehan kesenian ini adalah orang yang
memerankannya akan mampu memakan kaca serta rumput. Selain itu orang yang
memerankannya akan dicambuk seperti halnya menyambuk kuda. Biasanya kesenian
ini dipimpin oleh seorang pawang. Kesenian ini merupakan kesenian yang dalam
memainkannya membutuhkan keahlian yang sangat khusus karena merupakan kesenian
yang cukup berbahaya.
i.
Bajidoran


Bajidoran merupakan sebuah kesenian yang dalam memainkannya
hampir sama dengan permainan musik modern, cuma lagu yang dialunkan merupakan
lagu tradisional atau lagu daerah Jawa Barat serta alat-alat musik yang
digunakannya adalah alat-alat musik tradisional Jawa Barat seperti Gendang,
Goong, Saron, Bonang, Kacapi, Rebab, Jenglong serta Terompet.
Bajidoran ini biasanya ditampilkan dalam sebuah panggung
dalam acara pementasan atau acara pesta.
j.
Cianjuran
Cianjuran merupakan kesenian khas
Jawa Barat. Kesenian ini menampilkan nyanyian yang dibawakan oleh seorang
penyanyi, lagu yang dibawakannya pun merupakan lagu khas Jawa Barat. Masyarakat
Jawa Barat memberikan nama lain untuk nyanyian Cianjuran ini yaitu Mamaos yang
artinya bernyanyi.


k.
Kacapi Suling
Kacapi suling adalah kesenian yang berasal dari daerah Jawa
Barat, yaitu permainan alat musik tradisional yang hanya menggunakan Kacapi dan
Suling. Kacapi suling ini biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian sunda
yang pada umumnya nyanyian atau lagunya dibawakan oleh seorang penyanyi
perempuan, yang dalam bahasa sunda disebut Sinden.


l.
Reog
Di daerah Jawa Barat terdapat kesenian yang disebut Reog,
kesenian ini pada umumnya ditampilkan dengan bodoran, serta diiringi dengan
musik tradisional yang disebut Calung. Kesenian ini biasanya dimainkan oleh
beberapa orang yang mempunyai bakat melawak dan berbakat seni. Kesenian ini
ditampilkan dengan membawakan sebuah alur cerita yang kebanyakan cerita yang
dibawakan adalah cerita lucu atau lelucon.
B. Nilai Budaya Sunda
Budaya Sunda memiliki nilai-nilai tersendiri
yang berbeda dari budaya daerah lainnya. Masyarakat Sunda merupakan masyarakat
yang lembut, religius,dan spiritual. Mereka sesuai dengan pameo silihasih,
silihasah, dan silihasuh. Artinya yaitu masyarakat Sunda saling mengasihi,
saling memperbaiki diri, dan saling melindungi. Sebagian masyarakat Sunda masih
mempertahankan upacara adat asli Sunda. Mereka juga senang bergotong royong
sehingga terjalin kebersamaan antar warga. Nilai saling mengasihi yang
ditanamkan pada masyarakat Sunda ini dapat dikembangkan untuk kepentingan
masyarakat luas.
Setiap orang juga perlu saling memperbaiki
diri mereka dengan pendidikan dan berbagi ilmu. Tak sampai di sanasaja, tapi
masyarakat Sunda juga perlu saling melindungi untuk menjaga keselamatan
antarawarga. Secara garis besar nilai budaya Sunda ini memperlihatkan sisi
kebersamaan yang kuat karena tidak hanya untuk satu individu saja tapi untuk
tujuan kebersamaan.
C. Kelebihan Budaya Sunda
Setiap kebudayaan daerah membawa cirri khas masing-masing yang membuatnya berbeda satu sama lain, begitu juga dengan budaya sunda. Kebudayaan Sunda sendiri memberikan kontribusi
yang cukup besar bagi kebudayaan Indonesia. Kesenian Sunda misalnya sering mewakilkan Indonesia
di berbagai ajang dan acara internasional.
Angklung sendiri sudah dikenalkan di luar negeri, salah satunya di Amerika. Melalui kesenian Sunda tersebut, budaya Indonesia menjadi lebih dikenal oleh bangsa asing.
Budaya Sunda juga tidak hanya berupa kesenian seperti tari-tarian dan alat musik, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka memiliki watak dan nilai budaya.
Watak dan nilai budaya tersebut akan membentuk karakter masyarakat Sunda yang tersendiri. Mereka tergolong masyarakat yang membudayakan kerjasama satu sama lain. Hal tersebut sangat bagi bagi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini kebudayaan Sunda terus dipelihara dan dikembangkan baik itu di Jawa Barat
ataupun disebarkan kedaerah dan Negara lainnya.
D. Adat Istiadat Suku Sunda
Kata adat berasal dari
Bahasa Arab (dalam Bahasa Sunda: biasa, umum, lumrah), artinya: segala hal yang
senantiasa tetap atau sering diterapkan kepada manusia atau binatang yang
mempunyai nyawa. Kata adat, sedapat mungkin dipergunakan untuk menghaluskan perbuatan,
perlakuan, yang membuat kebaikan dengan orang lain, yang sama adatnya dan tata
cara pada umumnya misalnya yang terdapat dalam satu desa atau satu negara,
seagama maupun kebudayaannya. Apabila melanggar adat, misalnya dalam mengenakan
pakaian yang terbalik, pakaian yang terlalu bagus atau terlalu jelek. Begitu
juga dengan perkataan yang tidak sesuai dengan orang lain, duduk tidak sama
rendah, berdiri tidak sama tinggi dengan sesama. Maka yang bersangkutan telah
keluar dari lingkungan adat kelompoknya.
Adat istiadat yang
diwariskan leluhurnya pada masyarakat Sunda masih dipelihara dan dihormati.
Dalam daur hidup manusia dikenal upacara-upacara yang bersifat ritual adat
seperti: upacara adat Masa Kehamilan, Masa Kelahiran, Masa Anak-anak,
Perkawinan, Kematian dll. Demikian juga dalam kegiatan pertanian dan keagamaan
dikenal upacara adat yang unik dan menarik. Itu semua ditujukan sebagai
ungkapan rasa syukur dan mohon kesejahteraan dan keselamatan lahir bathin dunia
dan akhirat. Berikut adalah adat istiadat yang terdapat pada suku Sunda :
a.
Upacara adat pada masa kehamilan
1. Upacara mengandung empat
bulan
Dulu Masyarakat Jawa Barat apabila seorang
perempuan baru mengandung 2 atau 3 bulan belum disebut hamil, masih disebut
mengidam. Setelah lewat 3 bulan barulah disebut hamil. Upacara mengandung Tiga
Bulan dan Lima Bulan dilakukan sebagai pemberitahuan kepada tetangga dan
kerabat bahwa perempuan itu sudah betul-betul hamil. Namun sekarang
kecenderungan orang-orang melaksanakan upacara pada saat kehamilan menginjak
empat bulan, karena pada usia kehamilan empat bulan itulah saat ditiupkannya
roh pada cabang bayi oleh Allah SWT.
2. Upacara Mengandung tujuh
bulan/tingkeban
Upacara Tingkeban adalah upacara yang
diselenggarakan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Hal itu dilaksanakan
agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang melahirkan akan selamat.
Tingkeban berasal dari kata tingkeb artinya tutup, artinya adalah si ibu yang
sedang mengandung tujuh bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai empat
puluh hari sesudah persalinan, dan jangan bekerja terlalu berat karena bayi
yang dikandung sudah besar, hal ini untuk menghindari dari sesuatu yang tidak
diinginkan. Di dalam upacara ini biasa diadakan pengajian biasanya membaca
ayat-ayat Al-Quran surat Yusuf, surat Lukman dan surat Maryam. Di samping itu
dipersiapkan pula peralatan untuk upacara memandikan ibu hamil , dan yang utama
adalah rujak kanistren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang
hamil tadi dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji
secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai
bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Pada
guyuran ketujuh dimasukan belut sampai mengena pada perut si ibu hamil, hal ini
dimaksudkan agar bayi yang akan dilahirkan dapat berjalan lancar (licin seperti
belut). Bersamaan dengan jatuhnya belut, kelapa gading yang telah digambari
tokoh wayang oleh suaminya dibelah dengan golok. Hal ini dimaksudkan agar bayi
yang dikandung dan orang tuanya dapat berbuat baik lahir dan batin, seperti
keadaan kelapa gading warnanya elok, bila dibelah airnya bersih dan manis.
Itulah perumpamaan yang diharapkan bagi bayi yang dikandung supaya mendapatkan
keselamatan dunia-akhirat.
Sesudah selesai dimandikan biasanya ibu hamil
didandani dibawa menuju ke tempat rujak kanistren tadi yang sudah dipersiapkan.
Kemudian sang ibu menjual rujak itu kepada anak-anak dan para tamu yang hadir
dalam upacara itu, dan mereka membelinya dengan menggunakan talawengkar, yaitu
genteng yang sudah dibentuk bundar seperti koin. Sementara si ibu hamil menjual
rujak, suaminya membuang sisa peralatan mandi seperti air sisa dalam
jajambaran, belut, bunga, dsb. Semuanya itu harus dibuang di jalan simpang
empat atau simpang tiga.
3. Upacara mengandung
sembilan bulan
Upacara sembilan bulan dilaksanakan setelah usia
kandungan masuk sembilan bulan. Dalam upacara ini diadakan pengajian dengan
maksud agar bayi yang dikandung cepat lahir dengan selamat karena sudah
waktunya lahir. Dalam upacara ini dibuat bubur lolos, sebagai simbul dari
upacara ini yaitu supaya mendapat kemudahan waktu melahirkan, lolos. Bubur
lolos ini biasa dibagikan beserte nasi tumpeng atau makanan lainnya.
4. Upacara reuneuh
mundingeun
Upacara ini dilaksanakan apabila seorang
perempuan yang telah hamil tua tetapi belum melahirkan juga. Perempuan hamil
itu disebut reuneuh munding seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara
ini diselenggarakan agar si perempuan dapat melahirkan, jangan seperti kerbau
dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada pelaksanaannya leher
perempuan itu dikalungi kolotok sambil dibawa berkeliling oleh indung beurang
sambil mambaca doa. Apabila tidak ada kandang kerbau, maka kelilingilah rumah
sebanyak 7 x. Perempuan hamil itu harus dibuat seperti kerbau dan harus
menirukan suara kerbau, kemudian dimandikan oleh indung beurang di dalam rumah.
Di kota upacara ini sudah sangat jarang dilakukan.
b.
Upacara kelahiran dan masa bayi
1. Upacara memelihara
tembuni
Tembuni/placenta dipandang sebagai saudara bayi
karena itu tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus diadakan upacara waktu
menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Bersamaan dengan bayi dilahirkan,
tembuni (placenta) yang keluar biasanya dirawat dibersihkan dan dimasukan ke
dalam pendil dicampuri bumbu-bumbu garam, asam dan gula merah lalu ditutup
memakai kain putih yang telah diberi udara melalui bambu kecil (elekan). Pendil
diemban dengan kain panjang dan dipayungi, biasanya oleh seorang paraji untuk
dikuburkan di halaman rumah atau dekat rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke
sungai secara adat. Upacara penguburan tembuni disertai pembacaan doa selamat
dan menyampaikan hadiah atau tawasulan kepada Syeh Abdulkadir Jaelani dan ahli
kubur. Di dekat kuburan tembuni itu dinyalakan cempor/pelita sampai tali pusat
bayi lepas dari perutnya. Upacara tembuni itu dilaksanakan agar bayi selamat
dan kelak akan bahagia.
2. Upacara nenjrag bumi
Upacara ini adalah upacara memukul alu bumi
sebanyak tujuh kali di dekat bayi. Pada saat pelaksanaannya bayi di baringkan
di atas bambu yang telah di belah-belah, kemudian indung beurang menghentakkan
kakinya di dekat bayi tersebut. Upacara ini diselenggarakan agar ketika bayi
itu tumbuh dewasa ia tidak mudah terkejut atau ketakutan.
3. Upacara puput puseur
Ketika bayi telah terlepas dari tali pusatnya
biasanya diadakan selamatan. Tali pusat yang telah terlepas itu dimasukkan ke
dalam kanjut kundang oleh indung beurang. Kemudian pusar bayi ditutup dengan
logam yang telah dibungkus kain kasa dan kapas yang kemudian diikat pada perut
bayi, maksudnya agar pusat bayi tidak menonjol ke luar. Ada juga pada saat
upacara ini dilaksanakan sekaligus dengan pemberian nama bayi. Pada upacara ini
dibacakan doa selamat, dan disediakan bubur merah bubur putih. Ada kepercayaan
bahwa tali pusat (tali ari-ari) termasuk saudara bayi juga yang harus
dipelihara dengan sungguh-sungguh. Adapun saudara bayi yang tiga lagi ialah
tembuni, pembungkus, dan kakawah. Tali ari, tembuni, pembungkus, dan kakawah
biasa disebut dulur opat kalima pancer, yaitu empat bersaudara dan kelimanya
sebagai pusatnya ialah bayi itu. Kesemuanya itu harus dipelihara dengan baik
agar bayi itu kelak setelah dewasa dapat hidup rukun dengan saudara-saudaranya
(kakak dan adiknya) sehingga tercapailah kebahagiaannya.
4. Upacara ekah
Ekah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu
“Aqiqatun” yang artinya anak kandung. Upacara ekah adalah upacara ekah adalah
ungkapan rasa syukur karena telah diberikan anak oleh Allah SWT.Pada
pelaksanaan upacara ini biasanya diselenggarakan setelah bayi berusia 7 hari,
atau 14 hari, dan boleh juga setelah 21 hari. Perlengkapan yang harus
disediakan adalah domba atau kambing untuk disembelih, jika anak laki-laki
dombanya harus dua (kecuali bagi yang tidak mampu cukup seekor), dan jika anak
perempuan hanya seekor saja. Domba yang akan disembelih untuk upacara Ekah itu
harus yang baik, yang memenuhi syarat untuk kurban. Selanjutnya domba itu
disembelih oleh ahlinya atau Ajengan dengan pembacaan doa selamat, dan setelah
itu dibagikan kepada tetangga.
5. Upacara nurunkeun
Upacara nurunkeun adalah upacara pertama kali
bayi di bawa ke halaman rumah, dan pemberitahuan kepada tetangga bahwa bayi
telah dapat dibawa berjalan-jalan. Upacara Nurun keun dilaksanakan setelah
tujuh hari upacara Puput Puseur. Pada pelaksanaannya biasa diadakan pengajian
untuk keselamatan dan sebagai hiburannya diadakan pohon tebu atau pohon pisang
yang digantungi aneka makanan, permainan anak-anak yang diletakan di ruang
tamu. Untuk diperebutkan oleh tetangga terutama anak-anak.
6. Upacara cukuran/marhaban
Upacara cukuran dimaksudkan untuk membersihkan
atau menyucikan rambut bayi dari segala macam najis. Upacara cukuran atau
marhabaan juga merupakan ungkapan syukuran atau terima kasih kepada Tuhan YME
yang telah mengkaruniakan seorang anak yang telah lahir dengan selamat. Upacara
cukuran dilaksanakan pada saat bayi berumur 40 hari. Pada pelaksanaannya bayi
dibaringkan di tengah-tengah para undangan disertai perlengkapan bokor yang
diisi air kembang 7 rupa dan gunting yang digantungi perhiasan emas berupa
kalung, cincin atau gelang untuk mencukur rambut bayi. Pada saat itu mulailah
para undangan berdo’a dan berjanji atau disebut marhaban atau pujian, yaitu
memuji sifat-sifat nabi Muhammad saw. dan membacakan doa yang mempunyai makna selamat
lahir bathin dunia akhirat. Pada saat marhabaan itulah rambut bayi digunting
sedikit oleh beberapa orang yang berdoa pada saat itu.
7. Upacara turun taneuh
Upacara Turun Taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan
kakinya ke tanah, diselenggarakan setelah bayi itu dapat merangkak atau
melangkah sedikit-sedikit. Upacara ini dimaksudkan agar si anak mengetahui
keduniawian dan untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak, apakah
akan menjadi petani, pedagang, atau akan menjadi orang yang berpangkat.
Perlengkapan yang disediakan harus lebih lengkap dari upacara
Nurunkeun, selain aneka makanan juga disediakan kain panjang untuk menggendong,
tikar atau taplak putih, padi segenggam, perhiasan emas (kalung, gelang,
cincin), uang yang terdiri dari uang lembaran ratusan, rebuan, dan puluh
ribuan. Jalannya upacara, apabila para undangan telah berkumpul diadakan doa
selamat, setelah itu bayi digendong dan dibawa ke luar rumah.
Di halaman rumah telah dipersiapkan aneka makanan, perhiasan dan
uang yang disimpan di atas kain putih, selanjutnya kaki si anak diinjakan pada
padi/ makanan, emas, dan uang, hal ini dimaksudkan agar si anak kelak pintar
mencari nafkah. Kemudian anak itu dilepaskan di atas barang-barang tadi dan
dibiarkan merangkak sendiri, para undangan memperhatikan barang apa yang
pertama kali dipegangnya. Jika anak itu memegang padi, hal itu menandakan anak
itu kelak menjadi petani. Jika yang dipegang itu uang, menandakan anak itu
kelak menjadi saudagar/pengusaha. Demikian pula apabila yang dipegangnya emas,
menandakan anak itu kelak akan menjadi orang yang berpangkat.
c.
Upacara masa kanak-kanak
1. Upacara Gusuran
Gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus.
Maksud upacara Gusaran ialah agar gigi anak perempuan itu rata dan terutama
agar bertambah cantik. Upacara Gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan
sudah berusia tujuh tahun. Jalannya upacara, anak perempuan setelah didandani duduk
di antara para undangan, selanjutnya membacakan doa dan salawat kepada Nabi
Muhammad SAW. Kemudian Indung beurang melaksanakan gusaran terhadap anak
perempuan itu, setelah selesai lalu dibawa ke tangga rumah untuk disawer
(dinasihati melalui syair lagu). Selesai disawer, kemudian dilanjutkan dengan
makan-makan. Biasanya dalam upacara Gusaran juga dilaksanakan tindikan, yaitu
melubangi daun telinga untuk memasang anting-anting, agar tampak lebih cantik.
2. Upacara sepitan/sunatan
Upacara sunatan/khitanan dilakukan dengan maksud agar alat
vitalnya bersih dari najis . Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap
telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai umat Islam. Upacara Sepitan
anak perempuan diselenggarakan pada waktu anak itu masih kecil atau masih bayi.
Upacara sunatan diselenggarakan biasanya jika anak laki-laki menginjak usia 6
tahun. Dalam upacara sunatan selain paraji sunat, juga diundang para tetangga,
handai tolan dan kerabat. Pada pelaksanaannya, pagi-pagi sekali anak yang akan
disunat dimandikan atau direndam di kolam sampai menggigil (kini hal semacam
itu jarang dilakukan lagi berhubung teknologi kesehatan sudah berkembang),
kemudian dipangku dibawa ke halaman rumah untuk disunat oleh paraji sunat
(bengkong), banyak orang yang menyaksikan diantaranya ada yang memegang ayam
jantan untuk disembelih, ada yang memegang petasan dan macam-macam tetabuhan
sambil menyanyikan marhaba. Bersamaan dengan anak itu disunati, ayam jantan
disembelih sebagai bela, petasan disulut, dan tetabuhan dibunyikan . Kemudian
anak yang telah disunat dibawa ke dalam rumah untuk diobati oleh paraji sunat.
Tidak lama setelah itu para undangan pun berdatangan. Mereka memberikan uang/
nyecep kepada anak yang disunat itu agar bergembira dan dapat melupakan rasa
sakitnya. Pada acara ini ada pula yang menyelenggarakan hiburan, seperti wayang
golek, tarian dan sebagainya.
d.
Upacara adat perkawinan
Upacara adat perkawinan
dapat diurutkan dari adat sebelum akad nikah, saat akad nikah dan setelah nikah.
1. Sebelum akad nikah
a.
Neundeun Omong : yaitu kunjungan orang tua
jejaka kepada orang tua si gadis untuk bersilaturahmi dan menyimpan pesan bahwa
kelak anak gadisnya akan dilamar.
b.
Ngalamar : nanyaan atau nyeureuhan yaitu
kunjungan orang tua jejaka untuk meminang/melamar si
gadis, dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu
penikahannya. Sebagai acara penutup dalam ngalamar ini si pelamar memberikan
uang sekedarnya kepada orang tua si gadis sebagai panyangcang atau pengikat,
kadang-kadang dilengkapi pula dengan sirih pinang selengkapnya disertai kue-kue
& buah-buahan. Mulai saat itu si gadis telah terikat / bertunangan.
c.
Seserahan: yaitu menyerahkan calon pengantin pria kepada calon mertuanya
untuk dikawinkan kepada si gadis. Pada acara ini biasa dihadiri oleh para
kerabat terdekat, di samping itu calon pengantin pria juga menyerahkan
barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan perlengkapan
wanita, dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon pengantin
pria. Upacara ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari perkawinan atau adapula
yang melaksanakan pada hari perkawinan sebelum akad nikah dimulai.
d.
Ngeuyeuk Seureuh: artinya mengerjakan dan
mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. Upacara ini dilakukan sehari sebelum
hari perkawinan, yang menghadiri upacara ini adalah kedua calon pengantin,
orang tua calon pengantin dan para undangan yang telah dewasa. Upacara dipimpin
oleh seorang pengetua, benda perlengkapan untuk upacara ini seperti sirih
beranting, setandan buah pinang, mayang pinang, tembakau, kasang jinem/kain,
elekan, dll semuanya mengandung makna/perlambang dalam kehidupan berumah
tangga. Upacara ngeuyeuk seureuh dimaksudkan untuk menasihati kedua calon
mempelai tentang pandangan hidup dan cara menjalankan kehidupan berumah tangga
berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan selamat.
2. Upacara akad nikah
Upacara perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam agama Islam dan adat. Setelah
dilakukan ijab-qobul dengan baik selanjutnya mempelai pria membacakan talek,
yang bermakna ‘janji’ dan menandatangani surat nikah. Acara di akhiri dengan
penyerahan mas kawin oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.
3. Upacara setelah akad
nikah
a)
Munjungan/sungkeman : yaitu kedua mempelai
sungkem kepada kedua tua untuk memohon doa restu.
b)
Upacara Sawer (Nyawer): perlengkapan yang
diperlukan adalah sebuah bokor yang berisi beras kuning, uang kecil (receh)
/logam, bunga, dua buah tektek (lipatan sirih yang berisi ramuan untuk menyirih),
dan permen. Pada pelaksanaannya kedua mempelai duduk di halaman rumah di bawah
cucuran atap (panyaweran), upacara dipimpin oleh juru sawer. Juru sawer
menaburkan isi bokor tadi kepada kedua pengantin dan para undangan sebagai
selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Adapun makna dari upacara
nyawer tersurat dalam syair yang ditembangkan juru sawer, intinya adalah
memberikan nasehat kepada kedua mempelai agar saling mengasihani, dan
mendo’akan agar kedua mempelai mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam
membina rumah tangganya, hidup rukun sampai di akhir hayatnya.
c)
Upacara Nincak Endog : atau upacara injak telur
yaitu setelah upacara nyawer, kedua mempelai mendekati tangga rumah , di sana
telah tersedia perlengkapan seperti sebuah ajug/lilin, seikat harupat (sagar
enau) berisikan 7 batang, sebuah tunjangan atau barera (alat tenun tradisional)
yang diikat kain tenun poleng, sebuah elekan, sebutir telur ayam mentah, sebuah
kendi berisi air, dan batu pipisan, semua perlengkapan ini mempunyai
perlambang. Dalam pelaksanaannya lilin dinyalakan, mempelai wanita membakar
ujung harupat selanjutnya dibuang, lalu mempelai pria menginjak telur, setelah
itu kakinya ditaruh di atas batu pipisan untuk dibasuh air kendi oleh mempelai
wanita dan kendinya langsung dihempaskan ke tanah hingga hancur. Makna dari
upacara ini adalah menggambarkan pengabdian seorang istri kepada suaminya.
d)
Upacara Buka Pintu : upacara ini dilaksanakan
setelah upacara nincak endog, mempelai wanita masuk ke dalam rumah sedangkan
mempelai pria menunggu di luar, hal ini menunjukan bahwa mempelai wanita belum
mau membukakan pintu sebelum mempelai pria kedengaran mengucapkan sahadat.
Maksud upacara ini untuk meyakinkan kebenarannya beragama Islam. Setelah
membacakan sahadat pintu dibuka dan mempelai pria dipersilakan masuk.
e)
Upacara Huap Lingkung : Kedua mempelai duduk
bersanding, yang wanita di sebelah kiri pria, di depan mempelai telah tersedia
adep-adep yaitu nasi kuning dan bakakak ayam (panggang ayam yang bagian dadanya
dibelah dua). Mula-mula bakakak ayam dipegang kedua mempelai lalu saling tarik
menarik hingga menjadi dua. Siapa yang mendapatkan bagian terbesar dialah yang
akan memperoleh rejeki besar diantara keduanya. Setelah itu kedua mempelai huap
lingkung , saling menyuapi. Upacara ini dimaksudkan agar kedua mempelai harus
saling memberi tanpa batas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Sehabis
upacara huap lingkung kedua mempelai dipersilakan duduk di pelaminan diapit kedua
orang tua mempelai untuk menerima ucapan selamat kepada pengantin.
e. Upacara adat kematian
Pada garis besarnya rangkaian upacara adat kematian dapat
digambarkan sebagai berikut: memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolatkan
mayat, menguburkan mayat, menyusur tanah dan tahlilan, yaitu pembacaan do’a dan
zikir kepada Allah swt. agar arwah orang yang baru meninggal dunia itu diampuni
segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, juga mendo’kan agar keluarga yang
ditinggalkannya tetap tabah dan beriman dalam menghadapi cobaan. Tahlilan
dilaksanakan di rumahnya, biasanya sore/malam hari pada hari pertama wafatnya
(poena), tiluna (tiga harinya), tujuhna (tujuh harinya), matangpuluh (empat
puluh harinya), natus (seratus hari), mendak taun (satu tahunnya), dan newu
(seribu harinya). Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
masyarakat sunda kaya akan adat istiadat dan tradisi berupa upacara-upacara
adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam memperingati suatu momen.
Upacara tersebut juga bisa sebagai rasa syukur terhadap Tuhan atas karunia dan
nikmatNya. Karena kebanyakan dari mereka percaya bila tidak diadakan
upacara-upacara tersebut maka akan pamali atau segala sesuatu yang dianggap
tabu bila tidak dikerjakan.Tradisi masyarakat sunda cenderung turun temurun
dari nenek moyang hingga ke cicit-cicitnya. mereka mengenalkan tradisi tersebut
dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Namun untuk masyarakat
pedesaan umumnya tradisi tersebut sangat kuat daripada masyarakat perkotaan.
Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih terbuka terhadap hal-hal baru
yang bisa mengubah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang turun temurun.
f. Munggahan, tradisi suku Sunda pada
bulan ramadhan


Orang
Sunda merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh tradisi yang mereka
miliki dan melestarikannya. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih
dilakukan adalah tradisi Munggahan. Tradisi ini merupakan bentuk syukur atas
akan datangnya bulan Ramadhan. Karena itulah pelaksanannya pun selalu diadakan
sehari sebelum dan saat hari pertama puasa. Selain itu, di setiap kota di Jawa
Barat mungkin memiliki sedikit perbedaan dalam menjalani tradisi ini, namun
tradisi ini adalah hal wajib bagi masyarakat Sunda. Salah satu kesamaannya
yakni berkumpulnya anggota keluarga untuk bersilaturahmi, berdoa bersama, dan
makan sahur bersama.
E. Makanan Khas Sunda
Makanan khas Sunda memang memiliki rasa yang enak, Sunda
bukan hanya terkenal dengan kebudayaan yang ramah tetapi juga terkenal dengan
berbagai makanannya. Berikut ialah makanan khas Sunda :
1.
Tahu
Sumedang
Sesuai dengan namanya,
makanan ini merupakan makanan olahan tahu khas Sumedang yang biasa dicampur
dengan cabai, ataupun yang lainnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2406815/original/099536500_1542083306-HL.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2406815/original/099536500_1542083306-HL.jpg)
2. Karedok
Merupakan
makanan khas daerah di Indonesia. Karedok dibuat dengan bahan-bahan sayuran
mentah antara lain; ketimun, tauge, kol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong.
Sedangkan sausnya adalah bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, bawang
putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula jawa, garam, dan terasi.

3. Perkedel Bondon
Perkedel
kentang yang dimasak atau digoreng di atas tungku api, dan bahan bakan untuk
menyalakan api/baranya menggunakan kayu atau arang. Mungkin cara memasaknya ini
lah yang membuat perkedel ini sangat nikmat disajikan panas panas dan dengan
sambal saja sudah cukup untuk menemani nasi sebagai lauk untuk bersantap.


4. Gepuk
Gepuk
adalah makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari daging sapi,terasa sedikit
manis dan gurih. Biasanya gepuk dibuat dengan daging sapi,yang diiris searah
dengan serat daging dan direbus setengah mateng, kemudian di pukul pukul hingga
agak empuk. Daging yang sudah empuk direndam kedalam bumbu yang dicampur dengan
santan.kemudian direbus kembali hingga air santan menyusut.Jika akan disajikan
gorenglah gepuk dengan sedikit minyak hingga kecokelatan dan angkat.Gepuk akan
lebih enak di santap dengan nasi hangat dan sambel yang kami sediakan.


5.
Colenak
Makanan
khas Sunda yag berikutnya dalah Colenak yang merupakan singkata dari dicocol
enak (Bahasa Sunda),merupakan makanan yang dibuat dari peuyeum (tape singkong)
yang dibakar kemudian disajikan dengan saus yang terbuat dari parutan kelapa
dan gula merah. Karena kandungan gula di dalam tape maka tape tersebut mudah
gosong, meski ini adalah bagian yang terenak bagi beberapa orang.


6.
Nasi Timbel
Merujuk kepada cara memasak
dengan membungkus nasi panas di dalam daun pisang. Panas nasi menjadikan aroma
daun pisang luruh dan menambah aroma nasi. Caranya hampir sama dengan membuat
lontong; ditekan, dipadatkan, dan digulung dengan daun pisang; biasnya
disajikan bersama beberapa pilihan lauk-pauk teman nasi seperti ayam, bebek, atau
merpati goreng, empal gepuk, jambal roti, tahu, tempe, sayur asem, lalab dan
sambal. Nasi timbel pada perkembangannya mengilhami resep nasi bakar.


7. Cireng
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2227836/original/016151400_1527239579-resep-cireng-bumbu-rujak.jpg)
Cireng (singkatan dari aci
goreng, bahasa Sunda untuk ‘tepung kanji goreng’) adalah makanan ringan yang
berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan
yang berbahan utama tepung kanji. Makanan ringan ini sangat populer di daerah
Priangan, dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa. Makanan ini cukup
terkenal pada era 80-an. Bahan makanan ini antara lain terdiri dari tepung
kanji, tepung terigu, air, merica bubuk, garam, bawang putih, kedelai, daun
bawang dan minyak goreng.
7. Misro
Misro
merupakan makanan khas dari Jawa Barat. Terbuat dari parutan singkong yang
bagian dalamnya diisi dengan gula merah kemudian digoreng, karena itulah
dinamai Misro yang merupakan kependekan dari amis di jero (bahasa Sunda,
artinya: manis di dalam). Bentuknya bulat. Makanan ini enak disantap saat
hangat.


F. Sistem
Kemasyarakatan / Organisasi Sosial
Dilihat dari sudut sejarah, organisasi sosial yang hidup dalam masyarakat
di jawa barat ada yang mempunyai ciri-ciri lembaga/organisasi tradisional dan
organisasi modern. Yang di maksud organisasi tradisional adalah organisasi yang
muncul sebagai hasil inisiatif dan kreatif masyarakat desa, yang didorong
oleh kebutuhan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya,sedangkan
organsasi modern adalah lahir karena sengaja di bentuk, biasanya dari pihak atas desa dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Oganisasi
tradisional yang masih banyak ditemui dan dilakukan masyarakat sunda adalah :
1.
Organisasi tradisional yang
merupakan ikatan hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah
seperti :
a.
Memaro yaitu bagian hasil panen
sama
b.
Mertelu yaitu bagian hasil panen 1
berbanding 2
c.
Mlayang yaitu bagian hasil panen
10 sangga untuk 3 bau sawah
d.
Hejoan yaitu peminjaman uang yang
dibayar dengan hasil panen
2. Organisasi tradisional yang erat hubungannya dengan kehidupan desa di
priangan :
a.
Hiras/ngahiras, biasanya ada dalam
mendirikan ruah, tandur dan hajatan
b.
Liliuran yaitu saling tukar tenaga
dalam sesuatu pekerjaan A : B atau B : A
c.
Kondangan/Ondangan/Uleman,
biasanya terjadi dalam acara syukuran
3. Organisasi tradisional didasarkan atas kepentingan ekonomi, seperti :
a.
Sistem ijon yaitu peminjaman padi
pada musim paceklik dan di bayar pada musim panen dengan bunga tinggi.
b.
Sitem nyambat yaitu permintaan bantuan tenaga
dari tetangga dengan imbalan materi
c.
Sistem ceblokan yaitu sistem
kontrak penggarap sawah oleh satu kelompok petani sampai panen dan hasil panen
di bagi sesuai kesepakatan.
d.
Sistem pajegan yaitu siste kontrak tidak
sampai panen
e. Sistem sewa tanah yaitu menyewakan tanah kepada pemilik modal karena kebutuhan tertentu.
G. Bahasa dan Religius
Bahasa Sunda juga mengenal tingkatan dalam bahasa, yaitu
unda-usuk bahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial antara lain
yaitu:
1.
Bahasa Sunda lemes (halus) yaitu dipergunakan untuk
berbicara dengan orang tua, orang yang dituakan atau disegani.
2. Bahasa Sunda sedang yaitu digunakan antara
orang yang setaraf, baik usia maupun status sosialnya.
3.
Bahasa Sunda kasar yaitu digunakan
oleh atasan kepada bawahan, atau kepada orang yang status sosialnya lebih
rendah.
Religius masyarakat Sunda :
Sebagian
besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam, namun ada pula yang beragama
kristen, Hindu, Budha, dll. Mereka itu tergolong pemeluk agama yang taat,
karena bagi mereka kewajiban beribadah adalah prioritas utama. Contohnya dalam
menjalankan ibadah puasa, sholat lima waktu, serta berhaji bagi yang mampu.
Mereka juga masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Terdapat juga adanya
upacara-upacara yang berhubungan dengan salah satu fase dalam lingkaran hidup,
mendirikan rumah, menanam padi, dan lain-lainnya.
H.
Hal-hal yang Dianggap Tabu Oleh Masyarakat Sunda
Di setiap suku pasti ada hal yang di anggap tabu oleh
masyarakat nya, hal tabu yang terdapat di kebudayaan Sunda adalah sebagai
berikut :
1. Jangan makan tebu, sanksinya adalah
apabila suatu saat merantau maka akan mati di perantauan.
2. Tidak boleh bermain, bagi anak-anak
saat matahari terbenam, sanksinya adalah akan diganggu oleh makhluk halus.
3. Jangan makan yang masam-masam saat
matahari terbenam, sanksinya adalah akan ditinggal mati oleh ibunya.
4. Tidak boleh melangkahi padi (Nyi
Sri), sanksinya adalah akan mendapat penyakit yang disebabkan setan.
5. Tidak boleh memandikan kucing,
sanksinya adalah dapat berakibat datangnya hujan angin.
6. Jangan makan sirih yang kasar,
sanksinya adalah mati anak sulung.
7. Anak-anak tidak boleh bermain
lalangiran (tengkurap), sanksinya adalah akan mengakibatkan ibunya meninggal
dunia.
8. Perempuan tidak boleh meng-ayunkan
tangan kirinya, sanksinya adalah mengakibatkan masakan cepat hais.
9. Tidak boleh tidur di atas palupuh ,
sanksinya adalah tidak akan mendapat kebahagiaan.
10. Tidur tidak boleh terlentang di
bawah pangeret (Sepotong bambu atau kayu di antara dua buah tiang), sanksinya
adalah akan mengakibatkan mimpi buruk.
Tampak dalam beberapa petikan tabu di atas, klasifikasi
perbuatan dan akibat yang ditimbulkan bagi si pelanggar adalah tidak lebih dari
upaya agar etika sosial dan kesehatan tubuh berperan dalam penetapan tabu .
pengaruh dari perwajahan dunia gaib dan menyeramkan saat itu menjadi ide untuk
menjga agar telah dituangkan dalam tabu tetap terjaga.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kebudayaan adalah suatu
kebiasaan yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, adat istiadat, norma,
dan lain sebagainya.Kebudayaan Sunda sangat terkenal dengan kelembutannya, baik
dari tutur kata maupun ramah dalam menerima tamu dan sebagainya. Dalam kbudayaan
Sunda terdapat hal-hal tabu dan bagaimana adat istiadat di Sunda. Dalam
kebudayaan Sunda juga tercantum etos
dan watak Sunda, yakni cageur, bageur, bener, singer, dan pinter yang sudah lahir
sekitar jaman Salakanagara danTarumanagara. Lima kata itu diyakini mampu menghadapi
keterpurukan akibat penjajahan pada zaman itu.
B. Saran
Lestarikanlah kebudayaan
kita di Indonesia , bukan hanya budaya Sunda. Budaya-budaya di Indonesia sangat
unik dan menarik. Banyak turis berdatangan ke Indonesia untuk melihat atau
memahaminya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan bangga
dengan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki.
DAFTAR PUSTAKA
Adi.Adat Istiadat Suku Sunda.(adi37.blogspot.co.id/2012/12/adat-istiadat-suku-sunda.html.)
Diakses pada tanggal 07 Desember 2012 .
Frisca,Febriyani.Munggahan,Tradisi Suku Sunda untuk Sambut
Ramadhan. (www.bintang,com/lifestyle/read/2426115/munggahan-tradisi-suku-Sunda-untuk-sambut-ramadhan.) Diakses pada tanggal 01 Februari
2016.
Setiawan,Irvan.Tabu dalam Kebudayaan Sunda.(bpsnt-Bandung.blogspot.co.id/2009/07/tabu-dalam-kebudayaan-sunda.html#.WACxAfSedck.)
Diakses pada Bulan Juli 2009.
Komarudin,Hilman.Kebudayaan Sunda. (kebudayaansund.blogspot.co.id/2013/03/sistem-kekerabatan-dan-organisasi-sosial.html).
Diakses pada tanggal15 Maret 2013.
Kurnia,Dian.Sistem Organisasi masyarakat Sunda (Potret Kehidupan Urang Sunda). (https://diankurniaa.wordpress.com/2001/05/21/sistem-organisasi-masyarakat-sunda-potret-kehidupan-urang-Sunda/.) Diakses
pada tanggal 21 May 2011.
Https://tasik-cyber,blogspot.co.id/2014/08/gambar-dan-nama-pakaian-adat.html.


0 komentar:
Posting Komentar